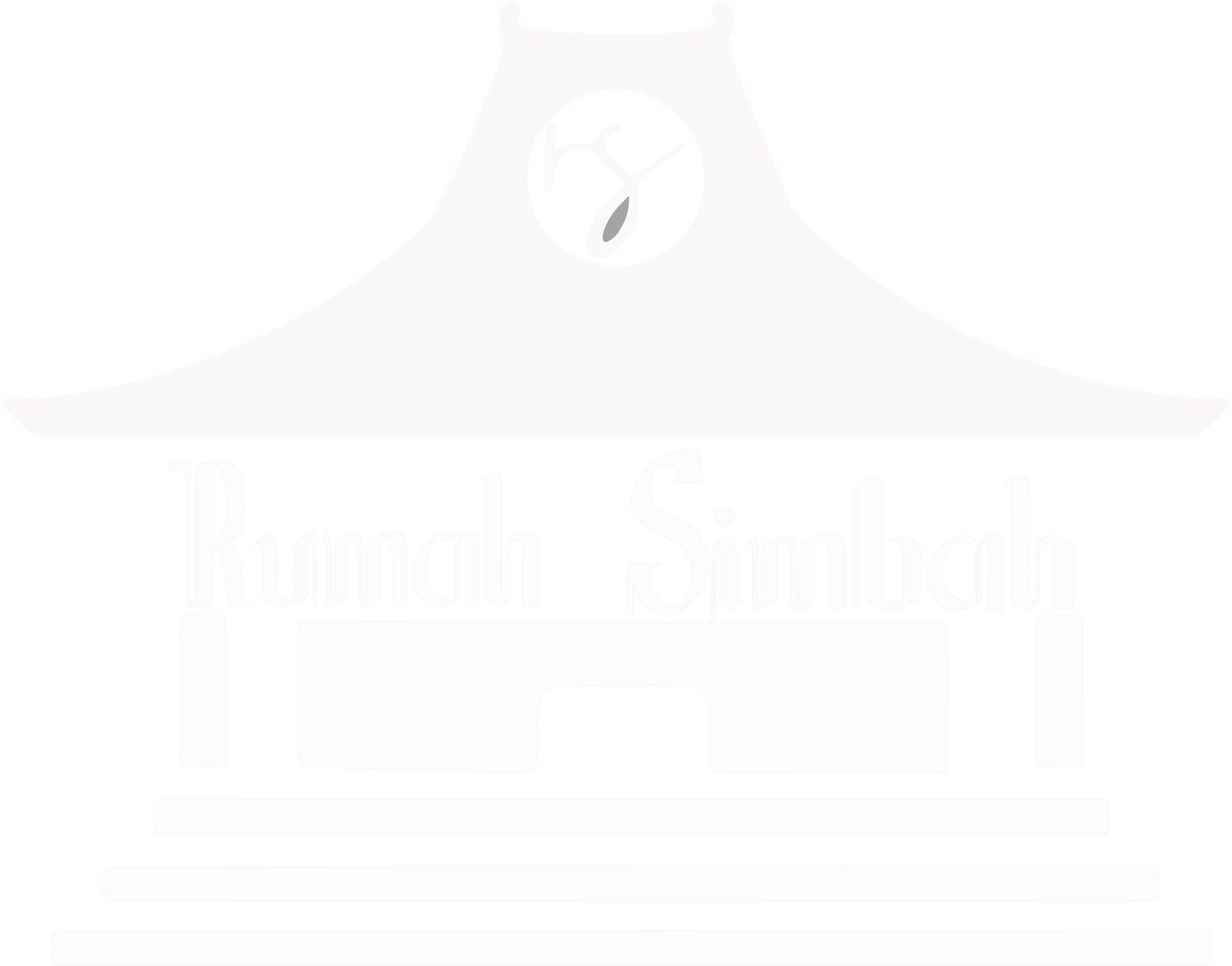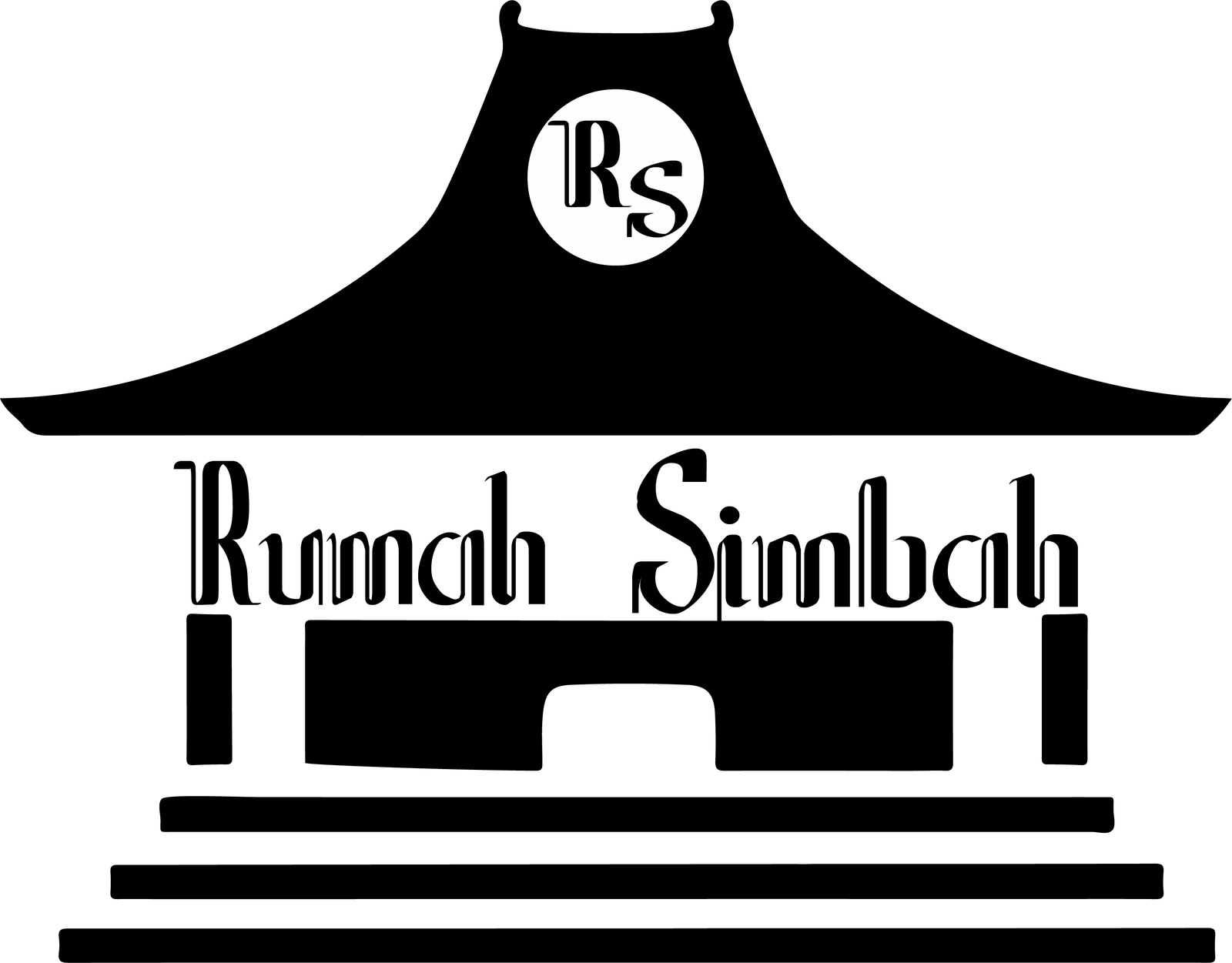Kita ini cepat sekali berkomentar. Sedikit-sedikit merasa paling benar. Ramai bicara, gemar menghakimi. Tapi saat diminta bertindak…sunyi.
Bogor, Jabar (Rumah Simbah)-Ruang publik Indonesia kian riuh. Bukan semata karena banyak persoalan, melainkan karena hampir semua hal diperlakukan sebagai bahan kegaduhan. Sedikit isu, langsung ramai. Sedikit beda pendapat, segera berisik. Seolah bangsa ini sedang berlomba menjadi komentator, bukan pencari solusi.
Fenomena ini melahirkan apa yang kerap disebut sebagai budaya “maido” atau kebiasaan menyalahkan. Segala sesuatu terasa salah, semua keputusan dianggap keliru, dan hampir tak ada ruang bagi jeda berpikir sebelum bereaksi. Media sosial menjadi panggung utama, tempat emosi lebih dulu berbicara sebelum nalar sempat duduk rapi.
Kegaduhan sering kali lahir bukan dari kepedulian yang tulus, melainkan dari dorongan untuk ikut bersuara agar tidak tertinggal arus. Pendapat disampaikan cepat, dangkal, dan berulang. Yang penting ramai, bukan benar. Yang utama viral, bukan bernilai.
Padahal, kritik sejatinya lahir dari kepedulian, bukan kemarahan semata. Kritik membutuhkan data, konteks, dan i’tikad untuk memperbaiki. Tanpa itu, yang terjadi hanyalah kebisingan kolektif yang melelahkan, namun tak membawa perubahan berarti.
Budaya gaduh juga berdampak pada cara bangsa ini memandang masalah. Segala sesuatu dipersempit menjadi hitam dan putih. Ruang dialog menyempit, digantikan saling serang dan saling ejek. Akhirnya, energi habis untuk berdebat, sementara substansi persoalan luput ditangani.
Menjadi bangsa yang dewasa bukan berarti berhenti bersuara, melainkan belajar mengelola suara. Kapan perlu lantang, kapan harus menimbang. Tidak semua hal harus dikomentari, dan tidak semua keresahan harus diteriakkan.
Di tengah hiruk-pikuk ini, barangkali yang kita butuhkan bukan suara yang lebih keras, melainkan pikiran yang lebih jernih. Bukan sekadar menjadi bangsa yang pandai bersuara, tetapi bangsa yang tahu kapan harus berbicara, dan untuk apa.(Siz)