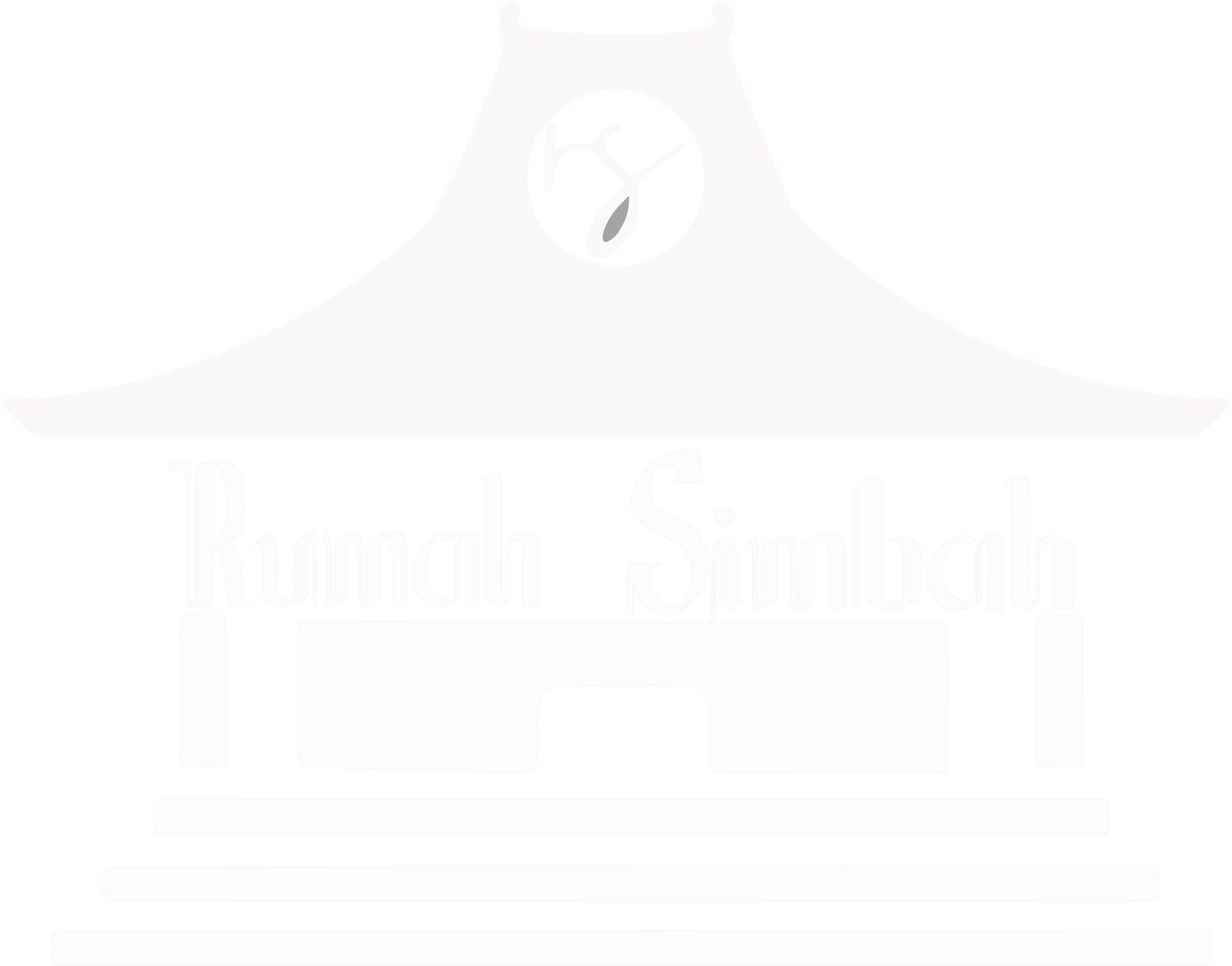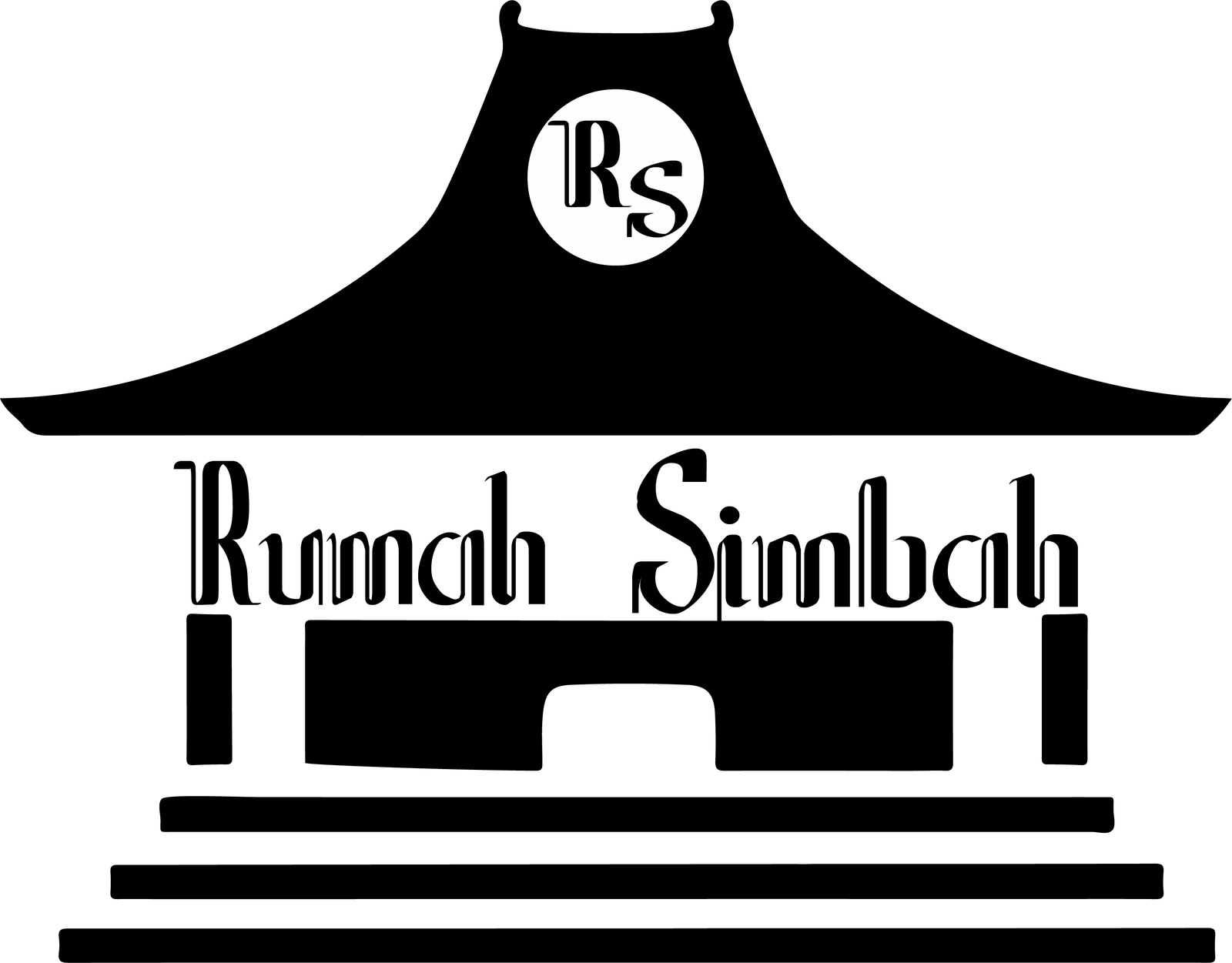Kita mengenal Bali sebagai tujuan liburan. Tapi lupa…di sini ada jutaan penduduk setempat yang tinggal. Bagaimana memahami Bali sebagai ruang hidup, video kiriman Vic-Nadya Izwa berikut menggambarkannya:

Badung, Bali (Rumah Simbah)-Bali nyaris selalu dibicarakan sebagai tujuan. Tujuan liburan. Tujuan pelarian. Tujuan mencari tenang, senang, dan sesekali validasi.
Poster-poster pariwisata menampilkan Bali sebagai ruang tanpa beban: pantai, senja, kafe estetik, senyum ramah. Seolah hidup di Bali adalah jeda panjang dari realitas. Padahal, bagi jutaan orang yang tinggal di dalamnya, Bali bukan jeda—ia adalah kehidupan itu sendiri.
Di sini orang bangun pagi bukan untuk berlibur, tapi untuk bekerja.
Untuk membayar sewa, menyekolahkan anak, menjaga warung, menyambut tamu, dan berharap hari ini cukup. Bali adalah ruang hidup yang berdenyut, dengan ritme yang sering kali tak terlihat oleh mata wisata.
Pariwisata memang membawa rezeki. Itu tak bisa disangkal.
Namun, ketika Bali terlalu lama dipandang hanya sebagai destinasi, ada risiko besar yang ikut mengendap: kehidupan warganya menjadi latar, bukan subjek. Rumah berubah fungsi. Ruang publik menyempit. Harga-harga naik pelan tapi pasti. Yang tinggal harus beradaptasi, sementara yang datang bebas memilih.
Ironisnya, semakin Bali mendunia, semakin banyak warganya merasa asing di tanah sendiri. Bukan karena benci pada wisata, tapi karena ruang hidup terasa makin sempit untuk sekadar bertahan. Yang indah dijual, yang berat dipikul diam-diam.
Tulisan ini tidak hendak menuding siapa pun. Tidak juga menolak pariwisata.
Ia hanya ingin mengajak kita berhenti sejenak—melihat Bali dari sudut yang jarang dipromosikan: sebagai rumah.
Sebab Bali bukan hanya tempat orang datang dan pergi.
Di sini ada orang-orang yang pulang setiap hari.
Dan ruang hidup, seharusnya, tak kalah penting dari tujuan wisata.(Vic-Nadya)